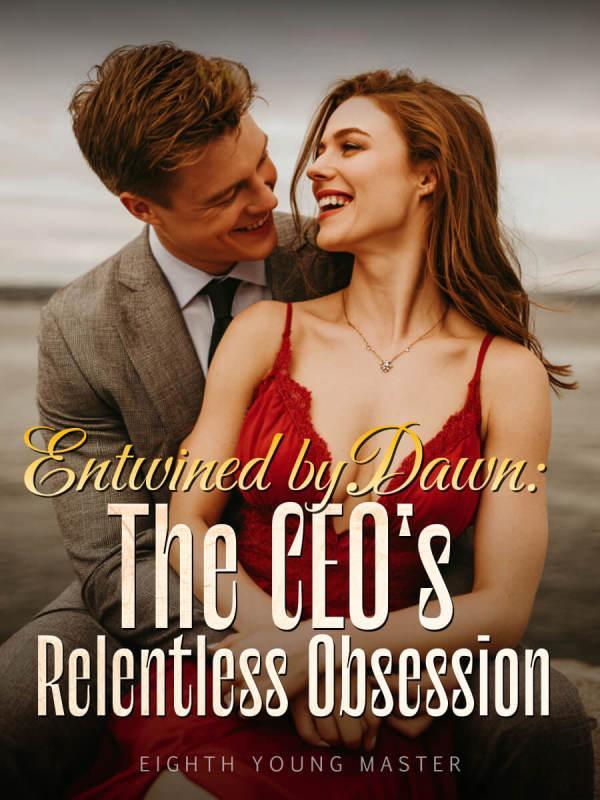The Shattered Light-Chapter 158: – Api Dalam Damai
Tiga hari setelah Benteng Pilar jatuh, dunia masih belum memutuskan bagaimana harus bersikap.
Langit pagi itu abu-abu, mendung menggantung seolah menanti arah angin perubahan. Di halaman reruntuhan, Lyra duduk di atas peti kayu, menyaksikan para penyintas membersihkan puing-puing. Suara palu dan gerutu bercampur dengan tangis anak-anak yang kembali mencari ayahnya.
Naerys datang dari belakang, membawa secangkir air hangat dan sepotong roti keras.
“Sarapan yang pantas untuk seorang pahlawan,” katanya dengan senyum miris.
Lyra mengambil cangkir itu, tidak langsung meminum.
“Kalau kita memang menang... kenapa tempat ini masih terasa seperti neraka?”
Naerys tidak menjawab. Ia duduk di sebelah Lyra, mengamati para mantan pengikut Ordo yang kini bekerja berdampingan dengan pasukan pemberontak. Beberapa dari mereka masih menolak menatap wajah Lyra, seakan dosa mereka terlalu tebal untuk dimaafkan.
“Karena tak ada kemenangan yang bersih,” akhirnya Naerys berkata. “Cuma perbaikan dari kekacauan sebelumnya.”
“Dan kita bertugas memperbaiki?”
“Kalau bukan kita, siapa lagi?”
Sebelum Lyra bisa membalas, langkah kaki tergesa terdengar. Seorang gadis berambut pendek datang berlari, napasnya terputus-putus.
“Kapten Lyra, ada... ada seseorang yang ingin bertemu. Dari Utara.”
Lyra dan Naerys saling pandang.
Di aula bekas perpustakaan, seorang pria berdiri di bawah jendela pecah. Jubahnya sederhana, tapi lambang di dadanya jelas: lambang Petak Cahaya Utara—faksi rahasia yang dikabarkan telah musnah sepuluh tahun lalu.
Pria itu menatap mereka dengan tenang. Rambutnya abu-abu, tapi matanya tajam seperti pisau.
“Lyra Kaelen. Naerys Thorne. Aku tak menyangka kalian masih hidup... atau lebih tepatnya, kalian yang menulis ulang sejarah.”
“Kau siapa?” tanya Lyra tegas.
“Namaku Tiras. Aku datang untuk menawarkan perdamaian... dan peringatan.”
Naerys menyilangkan tangan. “Perdamaian dari orang yang tak kami undang?”
“Atau mungkin, dari orang yang kalian lupa pernah kalian bantu lenyapkan,” balas Tiras.
Wajah Lyra mengeras. Ingatan itu datang—pengkhianatan di padang Esarn, markas Petak Cahaya dibakar karena dianggap terlalu ekstrem, bahkan oleh Ordo sendiri.
“Kami hanya menghentikan kekejaman,” jawab Lyra.
“Dan kini kalian yang memegang pedang.”
Diam. Tak ada yang membantah.
Tiras melangkah mendekat. Ia mengeluarkan gulungan perkamen, membuka segel berwarna darah.
“Di utara, reruntuhan Benteng Es mulai bergolak. Kami menangkap gerakan dari bayangan lama. Mereka menyebut dirinya Anak Matahari. Mereka mengklaim... kau yang mewariskan Relik Cahaya kepada mereka.”
Lyra membeku. “Mustahil.”
“Tapi terjadi. Dan mereka membawa panji-panji bertuliskan namamu. Menyebut dirimu sebagai ‘Ibu Kebangkitan.’”
Sore itu, di ruang rapat darurat, Lyra memandangi peta besar yang terbentang. Di sisi selatan, bekas wilayah Ordo perlahan berubah warna, tapi di utara, simbol baru muncul—matahari dengan lingkaran retak di tengah.
“Mereka pakai namaku untuk mengobarkan perang baru,” desis Lyra. “Untuk balas dendam.”
Alden yang baru tiba dari garis luar masuk dan menimpali, “Atau... mereka memang percaya kau akan kembali membakar sistem.”
“Aku tidak ingin jadi dewa,” katanya pelan.
“Tapi rakyat butuh wajah,” balas Alden. “Dan saat kekosongan lahir, mereka isi dengan harapan atau kebencian.”
Naerys memutar pisau kecilnya, lalu meletakkannya di meja. “Kita punya dua pilihan: biarkan mereka tumbuh jadi api yang tak terkendali... atau pergi sendiri dan bicara langsung pada mereka.”
“Pergi ke utara?” tanya Lyra. “Setelah semua ini?”
“Justru karena semua ini,” jawab Naerys. “Kalau kita menunggu, mereka akan membuat versimu sendiri... dan itu bisa jauh lebih berbahaya.”
Malam itu, Lyra duduk di beranda, memandangi langit yang dipenuhi awan gelap. Di tangannya, liontin Kaelen masih terasa hangat.
“Kau tahu? Kadang aku rindu kau marah padaku,” gumamnya. “Karena kau marah dengan alasan. Dunia ini marah tanpa tahu mengapa.”
Naerys mendekat, membawa dua selimut dan dua cangkir.
“Kita berangkat fajar. Tak ada jaminan apa pun.”
Lyra menatap temannya. “Kau yakin masih mau ikut?”
“Aku hanya percaya pada satu hal di dunia ini, Lyra,” jawab Naerys. “Dan itu adalah kau. Bahkan jika dunia berubah jadi abu, selama kau masih berdiri... aku tahu jalan itu belum habis.”
Lyra tak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, mendengar suara api unggun yang redup tertiup angin.
Di balik langit mendung, bayangan fajar mulai menembus. Bukan harapan, bukan juga kemenangan.
Hanya pengingat bahwa perang—dalam bentuk baru—sudah menunggu.