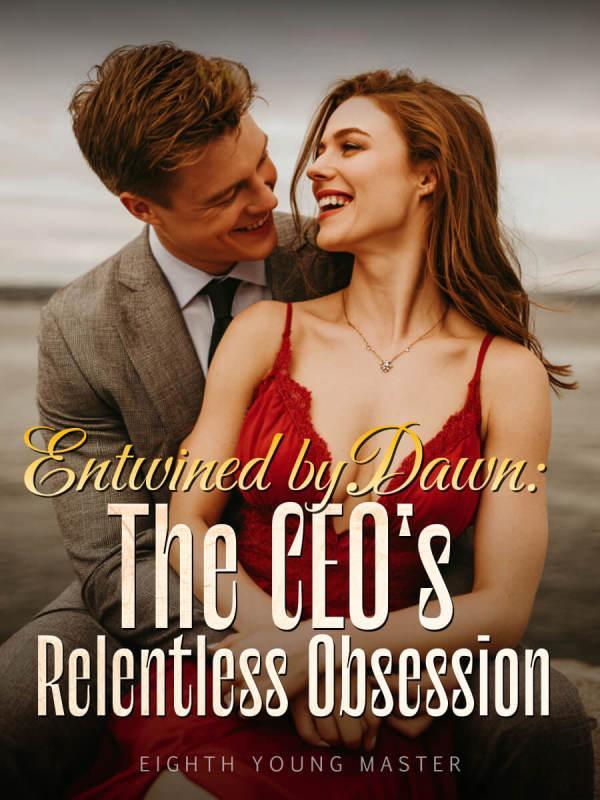The Shattered Light-Chapter 169: – Garis yang Mulai Retak
Suasana di kamp utama dingin dan kaku. Para prajurit sibuk membersihkan senjata dan menyusun kembali logistik setelah operasi malam yang nyaris sempurna. Namun bukan kemenangan yang mereka perbincangkan.
“Kaelen membiarkan mereka pergi?” salah satu komandan berbisik, suaranya penuh keraguan.
“Ia menyelamatkan anak-anak. Tapi membiarkan para penjaga hidup? Itu akan jadi preseden buruk,” timpal yang lain.
Di kejauhan, Kaelen berdiri di tenda utama, tangannya di belakang punggung, mata terpaku pada bendera pasukannya yang berkibar lesu. Langkah berat Alden memasuki tenda.
“Kau tahu mereka mulai meragukanmu,” kata Alden tanpa basa-basi.
Kaelen mengangguk. “Biar saja. Aku lebih suka kehilangan pasukan daripada kehilangan diriku sendiri.”
Alden mendekat, tatapannya tajam. “Tapi kau bisa kehilangan keduanya sekaligus. Kita sedang di tengah perang, bukan mimpi idealisme.”
Kaelen menoleh, perlahan. “Kalau aku membakar anak-anak hanya karena mereka ada di benteng musuh, apa bedanya aku dengan mereka?”
Alden terdiam.
Di sisi lain perkemahan, Lyra duduk memandangi coretan-coretan kecil yang digambar Imra di atas tanah. Gambar-gambar itu aneh—garis patah, lingkaran yang tak selesai, dan wajah-wajah tanpa mata.
“Kenapa kau gambar seperti ini, sayang?” tanya Lyra.
Imra mendongak. “Karena mereka semua hilang. Aku tidak ingat wajah mereka.”
Hati Lyra seolah ditarik keluar dari dadanya. Ia memeluk Imra, menahan air mata.
Di belakangnya, suara lembut terdengar.
“Kaelen pun mulai menggambar seperti itu... dulu,” ujar Eryon yang entah sejak kapan berdiri di dekat mereka.
Lyra menoleh cepat. “Apa maksudmu?”
Eryon menatap tanah. “Saat kekuatannya mulai tumbuh... dia mulai melupakan. Tak hanya nama atau wajah, tapi rasa. Saat aku masih... mendampingi pelatihan mereka, aku menyadarinya lebih dulu dari Varrok.”
Lyra berdiri, tegang. “Lalu kenapa kau tidak menghentikannya?”
“Aku pikir itu harga kecil untuk kekuatan besar. Ternyata aku salah besar.”
Di ruang strategi, ketegangan meledak.
“Pasukan kita kehilangan kepercayaan,” seru salah satu perwira muda. “Kami tidak mengikuti pemimpin yang tak berani mengambil keputusan tegas.”
Kaelen berdiri tenang. “Kalian ingin keputusan tegas? Baik. Siapa yang merasa bisa menggantikan posisiku, berdirilah. Aku tidak akan menghentikan kalian.”
Sunyi.
“Satu langkah ke depan. Aku tidak akan marah. Bahkan akan membantumu memimpin.”
Tak satu pun bergerak. Bahkan sang perwira muda menunduk perlahan.
Kaelen menatap mereka. “Keberanian bukan tentang menebas lebih cepat. Tapi tentang memilih siapa yang layak diselamatkan.”
Malamnya, Lyra dan Kaelen berbincang di luar tenda. Api unggun kecil menyala di antara mereka.
“Kau semakin dingin,” kata Lyra, pelan.
“Tidak. Aku hanya semakin sadar bahwa setiap keputusanku menelan sesuatu dariku.”
Lyra menarik napas panjang. “Aku takut... saat semua ini selesai, yang tersisa darimu hanya bayangan kosong.”
Kaelen memandangi api. “Kalau begitu... ingatkan aku. Genggam tanganku, bahkan saat aku tak tahu siapa kau.”
Lyra meraih tangannya, erat. “Janji itu hanya akan berarti jika kau berusaha mengingat.”
Pagi berikutnya, sebuah kabar tiba. Sebuah desa kecil di timur dibantai oleh sisa-sisa pasukan Ordo. Semua jejak menunjukkan pembalasan—mereka tahu Kaelen menyelamatkan anak-anak.
“Ini reaksi mereka. Ini permainan catur berdarah,” kata Alden di depan Kaelen.
Kaelen mengepalkan tangan. “Kita berangkat malam ini. Tapi tidak dengan serangan frontal. Aku ingin desa itu direbut tanpa api, tanpa pembantaian.”
“Kau minta keajaiban,” sahut Alden getir.
Kaelen menatapnya. “Aku minta kita tidak menjadi iblis yang sedang kita lawan.”
Lyra masuk ke tenda setelah semua pergi. Di atas meja, ia menemukan gulungan kecil—sebuah surat dari salah satu prajurit yang mundur.
“Kami mencintai komandan kami, tapi kami tak ingin menjadi simbol belas kasihan di tengah lautan kekejaman. Kami ingin menang, bukan dihormati.”
Lyra meremas surat itu. Tapi ia tahu: dunia Kaelen akan terus terbelah antara yang ingin damai, dan yang ingin menang. Dan keduanya tak bisa hidup berdampingan.